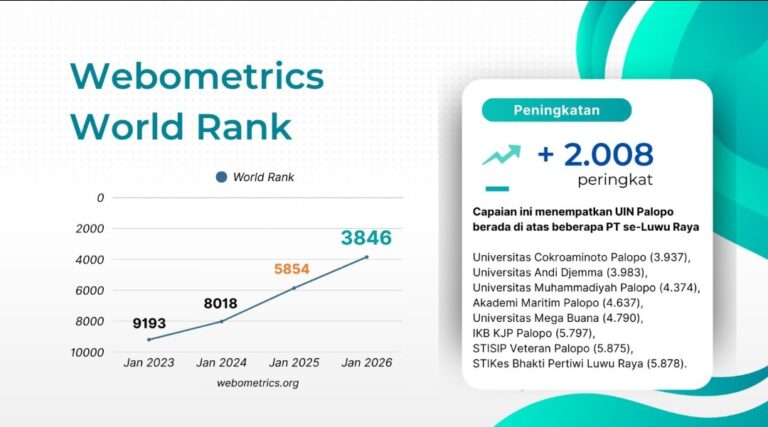Oleh: Wulandari
Hari Ibu kerap dirayakan dengan bunga, ucapan manis, dan unggahan penuh rasa terima kasih. Media sosial dipenuhi kata-kata indah yang menggambarkan kasih sayang dan pengorbanan seorang ibu. Semua itu tentu bermakna, tetapi sering kali berhenti di permukaan simbolik. Jarang kita benar-benar menyelami makna terdalam dari kehadiran seorang ibu: tentang kerja panjang yang senyap, tentang pengorbanan yang tak selalu terlihat, dan tentang pendidikan paling awal yang berlangsung jauh sebelum anak mengenal ruang kelas, buku pelajaran, atau guru formal.
Ibu adalah pendidik pertama, bahkan sebelum pendidikan itu disebut sebagai “pendidikan”. Sejak dalam kandungan, seorang ibu telah mengajarkan ketenangan melalui denyut jantungnya, rasa aman melalui kehadirannya, dan cinta melalui penerimaan tanpa syarat. Pendidikan ini tidak berlangsung dalam ruang yang riuh, tidak disertai kurikulum tertulis, dan tidak pernah diberi nilai angka. Namun justru dari sunyi itulah fondasi kepribadian seorang manusia mulai dibangun.
Sebagai mahasiswa pascasarjana di Universitas Islam Negeri Palopo, sekaligus guru dan konselor di Sekolah Menengah Kejuruan, saya kerap menyaksikan bagaimana jejak seorang ibu tertanam kuat dalam diri anak-anak, bahkan ketika mereka telah tumbuh menjadi remaja yang tampak mandiri. Dalam interaksi sehari-hari di ruang kelas maupun ruang konseling, terlihat jelas bahwa cara seorang siswa memandang dirinya, menghadapi kegagalan, atau menjalin relasi dengan orang lain sering kali berakar pada pengalaman awal bersama ibunya.
Ibu bukan sekadar sosok yang melahirkan secara biologis, melainkan figur yang pertama kali mengajarkan makna aman, sabar, dan dicintai. Dari ibu, seorang anak belajar bahwa dunia bisa menjadi tempat yang layak dipercaya. Nilai-nilai dasar ini kelak menentukan bagaimana seseorang membangun kepercayaan diri, mengelola emosi, serta memaknai relasi sosial dan spiritualnya. Ketika fondasi ini rapuh, dampaknya tidak hanya terlihat pada masa kanak-kanak, tetapi bisa terbawa hingga dewasa.
Dalam ajaran Islam, kedudukan ibu ditempatkan pada posisi yang sangat luhur. Bakti kepada ibu disebut berulang kali, bahkan didahulukan sebelum bakti kepada ayah. Penegasan ini seakan ingin menyampaikan bahwa peran ibu bukan sekadar peran domestik yang sempit, melainkan fondasi peradaban manusia. Islam tidak memuliakan ibu hanya dalam bahasa simbolik, tetapi mengakui secara nyata beban panjang yang dipikul seorang ibu: mengandung dalam kecemasan, melahirkan dalam risiko, dan mendidik dalam kelelahan yang sering tak bersuara.
Pengakuan ini selaras dengan temuan ilmu sosial dan psikologi perkembangan modern. Hubungan awal antara ibu dan anak terbukti membentuk rasa percaya dasar (basic trust), kestabilan emosi, serta keberanian anak dalam menghadapi dunia. Dari dekapan ibu, seorang anak belajar merasa cukup dan berharga. Dari tutur lembut dan respons empatik ibu, anak mengenal bahasa emosi dan empati jauh sebelum mengenal logika dan rasionalitas formal. Pendidikan karakter, dalam pengertian paling hakiki, bermula dari relasi ini.
Pengalaman di ruang kelas dan ruang konseling memperlihatkan kenyataan yang kerap luput dari perhatian. Banyak siswa yang tampak bermasalah secara perilaku atau prestasi, ternyata sedang memikul kekosongan emosional. Mereka tidak selalu kekurangan pengetahuan atau kecerdasan, tetapi kehilangan ruang untuk didengar dan dimengerti. Dalam banyak sesi konseling, yang paling mereka rindukan bukan hukuman yang adil atau nilai yang tinggi, melainkan kehadiran seorang ibu atau figur keibuan yang mau mendengar tanpa menghakimi dan memeluk tanpa syarat.
Di tengah arus digitalisasi dan perubahan sosial yang begitu cepat, peran ibu justru semakin berat. Anak-anak tumbuh di dunia yang ramai oleh informasi, tetapi sering merasa sepi secara emosional. Gawai menyediakan hiburan tanpa henti, tetapi tidak selalu menghadirkan kehangatan relasi. Dalam konteks ini, pendidikan karakter tidak cukup dititipkan pada sekolah atau kurikulum formal. Ia tumbuh dari keteladanan harian, dari cara ibu mengelola emosi, menyelesaikan konflik, membangun komunikasi, dan menanamkan makna hidup melalui tindakan-tindakan sederhana yang konsisten.
Ironisnya, peran sebesar ini sering tidak disertai dukungan yang memadai. Banyak ibu dituntut menjadi segalanya: pendidik utama, pengasuh penuh waktu, penjaga moral keluarga, sekaligus penopang ekonomi. Namun, tuntutan ini jarang diimbangi dengan dukungan sosial, kebijakan yang ramah keluarga, atau pengakuan struktural yang adil. Di titik inilah Hari Ibu seharusnya tidak berhenti pada seremoni tahunan. Ia perlu menjadi momen kesadaran kolektif bahwa memuliakan ibu berarti memastikan mereka tidak berjalan sendirian dalam menjalankan perannya.
Sebagai bagian dari komunitas akademik dan pendidik, refleksi Hari Ibu semestinya membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam: pembangunan manusia tidak dimulai dari ruang kuliah, ruang rapat kebijakan, atau dokumen kurikulum, tetapi dari rumah yang hangat secara emosional. Islam dan ilmu sosial bertemu pada satu kesimpulan yang sama,ibu adalah aktor utama dalam membentuk generasi yang beriman, berkarakter, dan tangguh menghadapi perubahan zaman.
Pada akhirnya, Hari Ibu mengajak kita untuk bertanya dengan jujur dan reflektif: sudahkah sistem pendidikan, kebijakan sosial, dan budaya kita benar-benar berpihak pada ibu? Sudahkah kita menciptakan lingkungan yang memungkinkan ibu mendidik dengan tenang, didukung, dan dihargai? Karena dari rahim, pelukan, doa, dan kata-kata sederhana seorang ibu, lahir manusia-manusia yang kelak mengisi ruang kelas, ruang publik, bahkan menulis sejarah peradaban.
Ibu mungkin bekerja dalam sunyi, tetapi dari sunyi itulah kehidupan belajar berbicara. Dampaknya tidak pernah singkat ia bergema panjang, lintas generasi, dan terus hidup sepanjang zaman.
Agen234
Agen234
Agen234
Berita Terkini
Artikel Terbaru
Berita Terbaru
Penerbangan
Berita Politik
Berita Politik
Software
Software Download
Download Aplikasi
Berita Terkini
News
Jasa PBN
Jasa Artikel
News
Breaking News
Berita